Negara Peradaban: Cina
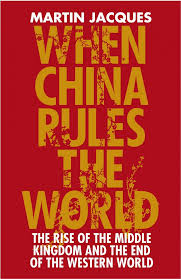 |
| When China Rules The World, sumber gambar: www.penguin.co.uk |
Cina, menurut standar semua negara
lain, adalah hewan paling ajaib. Selain ukurannya, Cina punya dua karakter luar
biasa, unik pula. Bukan sekadar sebuah
negara-bangsa, Cina juga merupakan sebuah peradaban dan benua.
Sesungguhnya, Cina menjadi sebuah negara bangsa relatif belum lama. Kapan
tepatnya terbuka untuk diperdebatkan: boleh jadi akhir abad kesembilan belas,
atau sesudah Revolusi 1911. Dalam pengertian ini—sama seperti Indonesia
dikatakan baru berumur setengah abad lebih sedikit, atau Jerman dan Italia yang
tak lebih dari satu abad—Cina adalah ciptaan sangat mutakhir. Tetapi, tentu
saja, ini omong kosong. Cina sudah ada
selama beberapa milenium, yang pasti lebih dari dua, mungkin malah tiga, ribu
tahun, walaupun rata-rata orang Cina suka membulatkan menjadi 5.000 tahun.
Ringkas kata, keberadaan Cina sebagai entitas yang dikenal dan berkesinambungan
jauh mendahului statusnya sebagai negara-bangsa. Dilihat dari segi kontinuitas
keberadaanya, Cina adalah negara tertua di dunia. Sudah ada sejak tahun 221 SM,
kalau bukan malah jauh sebelumnya. Ini bukan detail historis misterius, tetapi
memang begitulah cara orang Cina—bukan cuma kalangan elite, sopir taksi
juga—memandang negara mereka. Sering pandangan ini menyeruak dalam pembicaraan
seorang sopir, berikut rujukan pada Konfusius atau Mencius, barangkali dengan
sedikit bumbu puisi klasik. Ketika orang Cina menyebut “Cina” mereka lazimnya
tidak menunjuk pada negara atau bangsa melainkan peradaban Cina—sejarahnya,
deretan dinastinya, Konfusius, cara pikir, pola hubungan dan adat istiadat
mereka, guanxi (jaringan koneksi pribadi), keluarga, bakti kepada orang
tua, pemujaan leluhur, nilai-nilai, dan filsafat khas. Orang Cina tidak
memandang diri sehubungan dengan negara bangsa—seperti orang Eropa,
misalnya—melainkan sebagai sebuah negara-peradaban yang terkait dengan suatu
formasi geologis di mana negara-bangsa tak lebih dari tanah permukaan. Tidak
ada bangsa lain di dunia ini yang sedemikian terhubung dengan masa lalu mereka
dan yang bagi mereka masa lalu—bukan masa yang baru lalu tetapi yang jauh di
masa lalu—begitu relevan dan berarti. Semua negara lain bisa diibaratkan anak
ayam, rakyat dipisahkan dari masa lampau oleh keterpenggalan mencolok sejarah
mereka. Tetapi Cina tidak. Cina mengalami pergolakan dahsyat, serbuan dan
perpecahan, tetapi bagaimanapun juga garis kontinuitasnya tetap jelas, utuh dan
sangat dominan, tertanam kokoh di benak bangsa Cina selama masa sela dan
keterpenggalan.
Masyarakat Cina hidup di dalam dan
dengan sejarah mereka, betapapun jauhnya, dengan kadar sangat berbeda dari
masyarakat mana pun. “Negara lain mana di dunia ini,’ ujar sejarawan Wang
Gungwu, “yang bisa dikatakan hubungan luar negerinya selama dua ribu, atau
seribu tahun sajalah, ditulis nyaris sama hidupnya seperti saat ini?” Sarjana
Cina Jin Guantao mengemukakan, “Satu-satunya mode eksistensi [Cina] adalah
berpaling ke masa lalu. Tidak ada mekanisme yang bisa diterima dalam kebudayaan
bagi orang Cina untuk menghadapi masa kini tanpa bersandar pada ilham dan
kekuatan tradisi.” Sarjana Cina Huang Ping mengatakan:
Cina
adalah ... sejarah hidup. Di sini nyaris
setiap peristiwa dan proses yang terjadi sekarang terkait erat dengan sejarah,
dan tidak bisa dijelaskan tanpa memperhitungkan sejarah. Bukan cuma kalangan
intelektual, pegawai negeri dan pengusaha dan masyarakat awam pun punya
kesadaran sejarah yang kuat ... sesedikit apa pun pendidikan formal yang
dikecap orang, mereka hidup dalam sejarah dan bertindak sebagai ahli waris
serta juru bicara sejarah itu.
Penulis Tu Wei-ming mengungkapkan:
Memori
kolektif orang Cina sedemikian rupa hingga ketika membicarakan puisi Tu Fu
(712-70), Catatan Sejarah (teks sejarah sistematis Cina pertama, ditulis
antara 109 hingga 91 SM, menyampaikan sejarah Cina sejak masa Kaisar Kuning
hingga masa sang penulis) karya Sima Qian (meninggal sekitar 85 SM), Analek Konfusius, mereka merujuk pada tradisi
kumulatif yang dilestarikan dalam aksara Cina ... Sebuah perjumpaan dengan Tu
Fu, Sima Qian, atau Konfusius melalui simbol-simbol ideografis membangkitkan
sensasi realitas yang kehadirannya seolah-olah digoreskan selamanya dalam
naskah itu.
Kesadaran awal tentang Cina seperti
yang kita kenal sekarang muncul bersama dinasti Zhou, yang berkembang di sepanjang
Lembah Sungai Kuning pada akhir milenium kedua SM. Sebelum itu, sesungguhnya,
pada masa dinasti Shang, fondasi bagi Cina modern sudah mulai terbentuk dengan
sebuah bahasa ideografis, pemujaan leluhur dan gagasan tentang penguasa
tunggal. Sungguhpun demikian, peradaban Cina belum punya hakikat yang kokoh.
Hakikat ini menonjol beberapa abad kemudian melalui tulisan-tulisan Guru Kong,
Konghucu, atau Confucius nama Latinnya. Pada masa itu bahasa Cina sudah dipakai
di bidang pemerintahan dan pendidikan, dan gagasan tentang mandat Langit
sebagai prinsip pemerintahan turun-temurun tertanam kuat. Konfusius (551-479
SM) hidup sebelum periode Negara-negara Berperang (403-221 SM) ketika berbagai
negara tak henti-henti berperang satu sama lain. Kemenangan dinasti Qin
(221-206 SM) mengakhiri periode itu dan mencapai penyatuan banyak wilayah Cina,
dan kemunculan Cina modern bisa dikatakan bermula pada masa tersebut. Konfusius
tidak mendapat status yang tinggi dan tidak banyak dikenal semasa hidupnya,
justru setelah kematiannya dia menjadi satu-satunya penulis paling berpengaruh
selama sejarah Cina. Selama dua ribu tahun berikutnya Cina dibentuk oleh
argumen-argumen dan ajaran-ajaran moralnya, pemerintahan Cina diilhami oleh
prinsip-prinsip Konfusius dan Analek sudah mapan sebagai buku paling
penting dalam sejarah Cina. Konfusianisme adalah cara berpikir sinkretis yang
bersumber pada kepercayaan-kepercayaan lain, khususnya Taoisme dan Buddhisme,
tetapi ide-ide Konfusius sendiri tetap yang paling menonjol. Penekanannya pada
kearifan moral, pentingnya supremasi pemerintah dalam urusan manusia, dan pada
prioritas sangat tinggi bagi stabilitas dan persatuan, yang dibentuk oleh
pengalaman hidupnya dalam pergolakan dan instabilitas sebuah negara yang
terpecah-belah, mewarnai nilai-nilai fundamental peradaban Cina sejak saat itu.
Baru menjelang akhir abad kesembilan belas pengaruhnya mulai memudar, walaupun
selama kemelut abad kedua puluh—termasuk periode Komunis—pengaruh pemikirannya
tetap lestari dan jelas terasa. Ironisnya justru Mao Zedong, pemimpin Cina yang
paling membenci Konfusius, yang memungut tradisi Konfusian dalam bentuk maupun
isi Buku Merah Kecil yang ditulisnya.
Dua kontinuitas paling jelas dalam
peradaban Cina, yang semuanya bisa dirunut hingga Konfusius, berkenaan dengan
negara dan pendidikan. Negara selalu dipandang sebagai pengejawantahan dan
pengawal peradaban Cina yang, karena itulah, dalam era dinasti para kaisar dan
Komunis, memegang otoritas dan legitimasi sedemikian besar. Dari sekian gugus
tanggung jawabnya, negara terutama mengemban tugas luhur memelihara kesatuan
peradaban Cina. Tidak seperti dalam tradisi Barat, di Cina peran pemerintah
tidak mengenal batas dan sering diibaratkan seperti orang tua dengan kewenangan
tanpa batas. Paternalisme dipandang sebagai karakteristik pemerintahan yang
sangat dikehendaki dan mutlak diperlukan. Pada praktiknya negara tidak pernah
seperkasa yang dibayangkan, kendati demikian tidak ada keraguan mengenai
penghormatan dan penghargaan yang diperlihatkan orang Cina terhadap negara.
Persis seperti itu, konsep khas pendidikan dan pengasuhan anak Cina mengakar
berurat pada peradaban masa lalunya. Sejak masa Mencius (372-289 SM), murid
Konfusius, orang Cina selalu memandang sifat manusia secara optimis. Mereka
yakin bahwa pada dasarnya orang itu baik dan bahwa, dengan mengasuh anak sesuai
cara yang benar melalui pengasuhan dan pendidikan yang tepat, orang akan
memperoleh sikap, nilai-nilai dan disiplin diri yang benar. Di kelas, anak-anak
diharapkan memperlihatkan sikap hormat kepada guru dan, mengingat sangat
pentingnya sejarah, merujuk ke masa lalu sehubungan dengan kandungan pelajaran
mereka. Pendidikan dimuati otoritas dan penghormatan terhadap peradaban Cina,
dan guru bertindak selaku pembawa dan penyampai kearifan tersebut. Prioritas
tinggi diberikan bagi pelatihan dan teknik, setara dengan nilai-nilai
keterbukaan dan kreativitas di Barat, sehingga hasilnya adalah anak-anak Cina
yang sering mencapai tingkat komptenesi teknis jauh lebih tinggi dalam usia
sangat dini di bidang musik dan seni, misalnya, dibanding teman-teman Barat
mereka. Boleh jadi untuk sebagiannya ini berangkat dari penggunaan sebuah
bahasa ideografis, yang mensyaratkan pembelajaran menghafal ribuan aksara, dan
kemampuan mereproduksi akasara-aksara tersebut dengan kesempurnaan teknis.
Dalam menekankan kontinuitas peradaban
Cina, wajar jika ada keberatan bahwa selama kurun lebih dari dua milenium
terdapat kekacauan besar dan sering brutal serta diskontinuitas yang
menyebabkan tidak begitu miripnya Cina sekarang dengan dua ribu tahun silam.
Pada satu tataran, tentunya, ini benar. Cina sudah sedemikian berubah. Tetapi
pada tataran lain garis kontinuitas tetap bertahan dan terlihat jelas. Hal ini
tercermin dalam kesadaran diri orang Cina: di mana peradaban Cina—sebagaimana
terungkap dalam sejarah, cara berpikir, adat istiadat dan sopan santun,
pengobatan dan makanan tradisional, kaligrafi, peran pemerintah dan keluarga—tetap
menjadi rujukan pokok mereka. Wang Gungwu mengemukakan “apa yang pada
hakikatnya Cina adalah kontinuitas luar biasa yang tampaknya membuat peradaban
tersebut semakin unik selama berabad-abad.” Mengingat sejak 221 SM Cina sudah
dipersatukan selama 1.074 tahun, sebagian disatukan selama 673 tahun, dan
terpecah-pecah selama 470 tahun, walaupun mengalami beberapa penyerbuan besar
dan pendudukan selama milenium terakhir, hal tersebut bisa dikatakan luar
biasa. Sifat berbagai pendudukan tersebut justru memperlihatkan kekuatan
kebudayaan Cina dan ketahanan serta kontinuitas yang mendasarinya: dinasti
proto-Mongol Liao (907-1125 M) adalah dinasti non-Cina pertama di Cina utara;
dinasti Jin (1115-1234) berasal dari Mongolia; dinasti Yuan (1279-1368) juga
berdarah Mongol, sedangkan dinasti Qing (1644-1912) berasal dari Manchuria,
akan tetapi cepat atau lambat mereka menjadi orang asli dan ter-Cina-kan. Pada
masing-masing kurun tersebut kebudayaan Cina memperlihatkan diri jauh lebih
unggul ketimbang para penyerbunya. Bahkan “invasi” Buddhis awal dari India pada
abad pertama Masehi juga berujung dengan ter-Cina-kannya ajaran-ajaran Buddha
selama kurun ratusan tahun.
Tantangan Barat di sekitar tahun 1850
adalah tawaran yang sama sekali berbeda: aspek-aspek utama kebudayaan Barat,
terutama orientasi dan pengetahuan ilmiahnya, jelas mengungguli Konfusianisme
tradisional dan menyeretnya ke dalam sebuah krisis kian mendalam ketika orang
Cina enggan mengupayakan semacam rekonsiliasi antara nilai-nilai tradisional
dan Barat. Antara tahun 1911 dan 1949 hampir tidak ada institusi penting
(konstitusi, universitas, pers, Gereja, dan lain-lain) yang bertahan dalam
bentuk asalnya selama lebih dari satu generasi, karena sedemikian signifikan
dan awetnya watak kekokohan Cina. Barat menyodorkan asumsi-asumsi Cina yang
terdesentralisasi. Akhirnya, ketika semuanya gagal, Cina berpaling pada
Komunisme, atau lebih spesifik Maoisme, yang mengandung penolakan tegas
terhadap Konfusianisme. Meski begitu, selama periode Maois nilai-nilai dan cara
berpikir Konfusian tetap berpengaruh, meski dalam bentuk terselubung, dan bisa
dikatakan tetap merupakan nalar lazim rakyat. Sekarang pun, setelah berhasil
bangkit dari kemerosotan dan mengalami gegap gempita modernisasi, Cina masih
direpotkan oleh hubungan antara kebudayaan Cina dan Barat dan sejauh mana dirinya
mengalami Westernisasi. Sungguhpun demikian, melalui pergolakan, pembantaian,
kekacauan dan kelahiran kembali, Cina
tetap masih dikenali seperti sedia kala. Ketika Cina menapak naik selangkah
lagi, kepercayaan dirinya dilambungkan oleh berbagai capaian mutakhir,
pencarian maknanya tidak melulu bertumpu pada modernitas melainkan juga, dan
seperti biasanya, pada masa lalu peradabannya. Cara berpikir Konfusian, yang
tidak pernah punah itu, dihidupkan kembali dengan giat dan dicermati karena
bisa dipakai di masa kini, dan karena kemampuannya memberikan panduan moral.
Bagi banyak negara berkembang proses
modernisasi dicirikan oleh sebuah krisis identitas, kerap diperparah oleh
pengalaman kolonial, sebuah perasaan terkoyak di antara kebudayaan mereka
sendiri dan kebudayaan Barat, terkait dengan rasa rendah diri mengenai relatif
terbelakangnya mereka. Tentu saja orang Cina punya perasaan terhina, tetapi
tidak pernah mengenal rasa rendah diri yang sangat kuat dan melumpuhkan: mereka
selalu punya kesan kuat tentang apa arti menjadi orang Cina dan sangat bangga
dengan fakta itu. Kecinaan itu bahkan sedemikian kuat hingga mengaburkan dan
membayangi—bertolak belakang dengan yang terjadi di India,
misalnya—identitas-identitas kuat lain seperti daerah, kelas sosial dan bahasa.
Rasa memiliki ini mengakar pada masa lalu peradaban Cina, yang berfungsi
mengikat sebuah populasi sangat besar dengan perbedaan dialek, adat istiadat,
etnis, geografi, iklim, tingkat perkembangan ekonomi dan standar hidup. “Yang
menyatukan orang Cina,” kata Lucian Pye, “adalah pengertian mereka tentang
kebudayaan, ras dan peradaban, bukan identifikasi dengan bangsa sebagai sebuah
negara.”
Sehingga, memaparkan Cina dalam
pengertian sebuah negara-bangsa bisa dikatakan tidak tepat. “Cina adalah sebuah
peradaban,” menurut Pye, “yang menampilkan diri seolah-olah adalah sebuah
negara-bangsa.” Banyak sekali konsekuensi dari kenyataan bahwa sesungguhnya
Cina adalah sebuah negara-peradaban. Negara-peradaban ini melahirkan jenis
politik yang sangat berbeda dari yang dianut negara-bangsa konvensional, dan
persatuan, yang mengakar pada ide
tentang peradaban bukannya bangsa, menjadi prioritas tertinggi. Sebagai sebuah
negara-peradaban, Cina mewujudkan dan membolehkan pluralitas sistem, seperti dalam kasus Hong
Kong, yang tidak dikenal oleh negara-bangsa yang menghendaki dan memerlukan
tingkat homogenitas jauh lebih tinggi. Negara-peradaban melahirkan pengertian
tersendiri orang-orang Cina mengenai ras dan etnis, dengan ras Han kurang
lebihnya dianggap berdekatan dengan peradaban Cina kuno. Negara-peradaban
mewujudkan hubungan amat erat tidak hanya dengan sejarah relatif mutakhir Cina,
sebagaimana lazimnya kebanyakan negara-bangsa, melainkan, dan ini sangat jelas
terlihat, dengan setidak-tidaknya sejarah dua milenium yang terus-menerus
menyela dan berfungsi sebagai pedoman dan tolok ukur di masa sekarang.
Negara-peradaban inilah yang berfungsi sebagai pengingat terus-menerus bahwa
Cina adalah Kerajaan Tengah, dan karena itu, sebagai pusat dunia, menempati
kedudukan sangat berbeda dengan semua negara lain. Istilah “peradaban” umumnya
mengisyaratkan pengaruh sangat jauh dan tak langsung serta kehadiran yang
lembam dan pasif. Tetapi dalam kasus Cina yang hidup bukan hanya sejarah
melainkan juga peradaban itu sendiri: pengertian tentang sebuah peradaban yang
hidup memberi identitas utama dan konteks yang digunakan orang Cina memandang
negara mereka dan mendefinisikan diri.
Dari Martin Jacques, When China Rules The World: The Rise Of The Middle
Kingdom And The End Of The Western World, Allen Lane an imprint of Penguin
Books, h. 196 - 202.
Untuk versi yang sudah disunting dan, tentu saja, lebih baik silakan baca
bukunya
Judul : When China Rules The World Ketika
China Menguasai Dunia; Kebangkitan Dunia
Timur dan Akhir Dunia Barat.
Penerjemah : Noor Cholis (penyelia), Jarot Sumarwoto.
Penerbit : Penerbit Buku Kompas 2011



Comments
Post a Comment